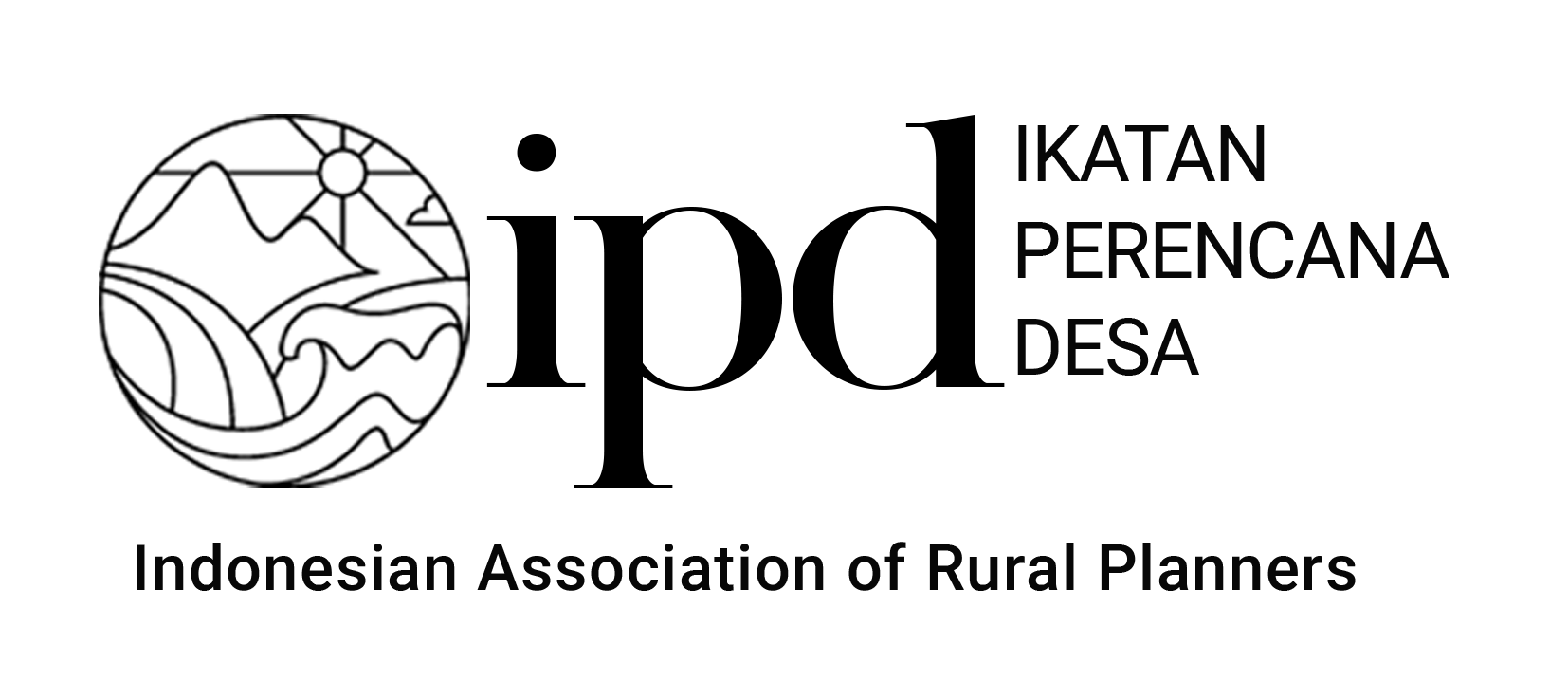Jebakan Geografis Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan di Indonesia terus menjadi masalah sosial yang krusial, meskipun negara ini telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Indonesia yang kini memiliki status sebagai negara berpenghasilan menengah dengan PDB yang melebihi USD 1 triliun (BPS, 2020), masih menghadapi kenyataan pahit di mana jutaan rakyatnya hidup dalam kondisi miskin, dengan ketimpangan antar daerah yang sangat mencolok. Ketimpangan ini tidak hanya bersifat ekonomi, namun juga terkubur dalam dimensi geografi dan spasial yang sangat memengaruhi upaya pengentasan kemiskinan. Isu ini, yang sudah diakui dalam literatur akademik, menunjukkan bahwa jebakan kemiskinan spasial---di mana daerah-daerah tertentu terperangkap dalam siklus kemiskinan karena kekurangan modal geografis---menjadi hambatan besar dalam strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia (Arif et al., 2025; Bird, 2019). Kasus Indonesia memberikan contoh nyata dari fenomena ini, di mana daerah-daerah terpencil di dataran tinggi dan pesisir lebih banyak terjebak dalam kemiskinan.
Penelitian ini memperkenalkan perspektif spasial dalam memandang kemiskinan di Indonesia, dengan tujuan untuk menyoroti peran penting modal geografis dalam mempertahankan kemiskinan. Modal geografis merujuk pada interaksi antara populasi manusia dan lingkungan fisik mereka, mencakup elemen-elemen seperti lokasi, infrastruktur, akses terhadap layanan, dan sumber daya alam (Jalan & Ravallion, 1997). Hal ini memengaruhi bagaimana aktivitas ekonomi terdistribusi, dan dalam konteks Indonesia, memainkan peran sentral dalam menentukan kesejahteraan atau stagnasi suatu wilayah di seluruh nusantara. Studi kami mengidentifikasi 26 wilayah di Indonesia yang terperangkap dalam kemiskinan spasial, dengan daerah dataran tinggi dan pesisir sebagai yang paling rentan. Daerah-daerah ini tidak hanya kekurangan modal geografis yang rendah, tetapi juga terisolasi dari dinamika ekonomi yang lebih luas di negara ini, yang semakin memperburuk tingkat kemiskinan mereka (Olivia et al., 2011).
Fitur geografis seperti wilayah dataran tinggi dan topografi pulau-pulau terbatas menghambat aksesibilitas, menciptakan hambatan dalam perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan integrasi ekonomi secara keseluruhan. Di Papua dan Papua Barat, misalnya, medan yang terjal dan infrastruktur yang kurang berkembang menghalangi akses terhadap layanan dasar, yang membuat penduduknya sulit keluar dari kemiskinan (Arif et al., 2025). Begitu juga daerah pesisir dan pulau-pulau seperti yang ada di Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Utara, yang menghadapi isolasi akibat pemisahan geografis oleh laut, semakin memperburuk kemiskinan mereka. Daerah-daerah ini yang bergantung pada sumber daya alam terbatas dan rentan terhadap gangguan akibat perubahan iklim, tidak mampu mendiversifikasi ekonomi mereka, yang memperburuk kerentanannya terhadap masalah ekonomi (Olivia et al., 2011).
Penelitian ini menggunakan berbagai teknik statistik, termasuk regresi berbobot secara geografis (GWR) dan sistem informasi geografis (GIS), untuk memetakan kemiskinan di seluruh Indonesia dan menyoroti korelasi antara tingkat kemiskinan dan modal geografis. Temuan menunjukkan bahwa jebakan kemiskinan spasial banyak terdapat di daerah-daerah dataran tinggi, di mana ketinggian dan buruknya infrastruktur sangat membatasi peluang ekonomi. Di daerah-daerah seperti Jayawijaya, Puncak Jaya, dan Mamberamo di Papua, tingkat kemiskinan yang tinggi erat kaitannya dengan medan yang sulit dan kurangnya konektivitas, yang semakin mengisolasi daerah-daerah ini dari peluang pembangunan (Arif et al., 2025).
Sebaliknya, daerah-daerah yang terletak di wilayah dataran rendah dengan infrastruktur dan konektivitas yang lebih baik, seperti Jakarta, Bali, dan Yogyakarta, menunjukkan penurunan yang signifikan dalam tingkat kemiskinan. Daerah-daerah ini mendapat keuntungan dari jaringan ekonomi yang lebih kuat, akses yang lebih baik ke pasar, dan tingkat modal geografis yang lebih tinggi, yang semuanya berkontribusi pada kemakmuran mereka (BPS, 2020). Perbedaan antara daerah-daerah ini dan mereka yang terperangkap dalam kemiskinan spasial menggambarkan perlunya intervensi yang terfokus dan spesifik yang mengatasi tantangan geografis yang dihadapi daerah-daerah yang terisolasi.
Implikasi kebijakan dari temuan ini sangat jelas. Untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia secara efektif, pendekatan yang lebih terfokus dan berbasis pada geografi perlu diadopsi. Pembuat kebijakan harus melampaui solusi ekonomi tradisional yang gagal mempertimbangkan faktor spasial yang berkontribusi pada kemiskinan. Strategi yang lebih holistik sangat dibutuhkan, yang mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas, dan dukungan untuk diversifikasi ekonomi di wilayah yang miskin. Investasi dalam infrastruktur transportasi dan digital dapat membantu mengintegrasikan daerah-daerah yang terisolasi ke dalam jaringan ekonomi yang lebih luas, membuka peluang untuk perdagangan, pendidikan, dan layanan kesehatan (Wang et al., 2021). Selain itu, kebijakan harus memprioritaskan wilayah yang diidentifikasi sebagai jebakan kemiskinan spasial, memastikan bahwa intervensi disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing daerah.
Selain infrastruktur, kebijakan juga harus fokus pada pengembangan modal manusia. Pendidikan dan pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan konteks ekonomi lokal dapat memberikan penduduk daerah miskin alat yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang berubah. Pendekatan ini sangat penting di daerah-daerah yang masih mengandalkan industri tradisional seperti pertanian, di mana industri modern belum berkembang. Program-program yang mempromosikan literasi digital dan kewirausahaan dapat membantu mendiversifikasi ekonomi lokal dan memberikan jalur pendapatan baru (Rahim et al., 2023).
Mengingat luasnya dan keragamannya geografi Indonesia, sangat penting bahwa upaya pengentasan kemiskinan disesuaikan dengan tantangan unik yang dihadapi oleh setiap daerah. Misalnya, daerah pesisir di Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat memerlukan intervensi yang mendukung pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, sementara daerah dataran tinggi di Papua dan Papua Barat membutuhkan kebijakan yang mengatasi tantangan infrastruktur dan aksesibilitas yang disebabkan oleh medan yang terjal. Intervensi yang disesuaikan ini dapat membantu memutus siklus kemiskinan dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.
Akhirnya, penelitian ini menekankan pentingnya mengakui modal geografis sebagai faktor penentu utama dalam upaya pengentasan kemiskinan. Meskipun pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan, kebijakan yang terfokus pada geografi yang memperhitungkan karakteristik lokal dapat membantu menciptakan hasil pembangunan yang lebih merata. Agar Indonesia dapat mengatasi jebakan kemiskinan spasial, pembuat kebijakan harus mengadopsi pendekatan yang lebih holistik terhadap pembangunan yang mengintegrasikan pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya akan mengurangi kemiskinan tetapi juga memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
Mengatasi jebakan kemiskinan spasial di Indonesia membutuhkan tindakan segera dari pemerintah. Tidak cukup hanya mengandalkan strategi pengurangan kemiskinan yang umum, melainkan pendekatan berbasis geografi diperlukan untuk memastikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan efektif dan berkelanjutan. Hanya dengan memfokuskan pada tantangan unik yang dihadapi daerah dataran tinggi dan pesisir, serta dengan berinvestasi dalam infrastruktur, pengembangan modal manusia, dan diversifikasi ekonomi, Indonesia dapat memutuskan siklus kemiskinan yang terus menghantui banyak warganya.
Referensi: Arif, M., Muta'ali, L., & Rijanta, R. (2025). Mapping poverty traps in Indonesia: A spatial perspective. Regional Statistics, 15(2), 1--24.
Untuk membaca opini lengkapnya, kunjungi Kompasiana.