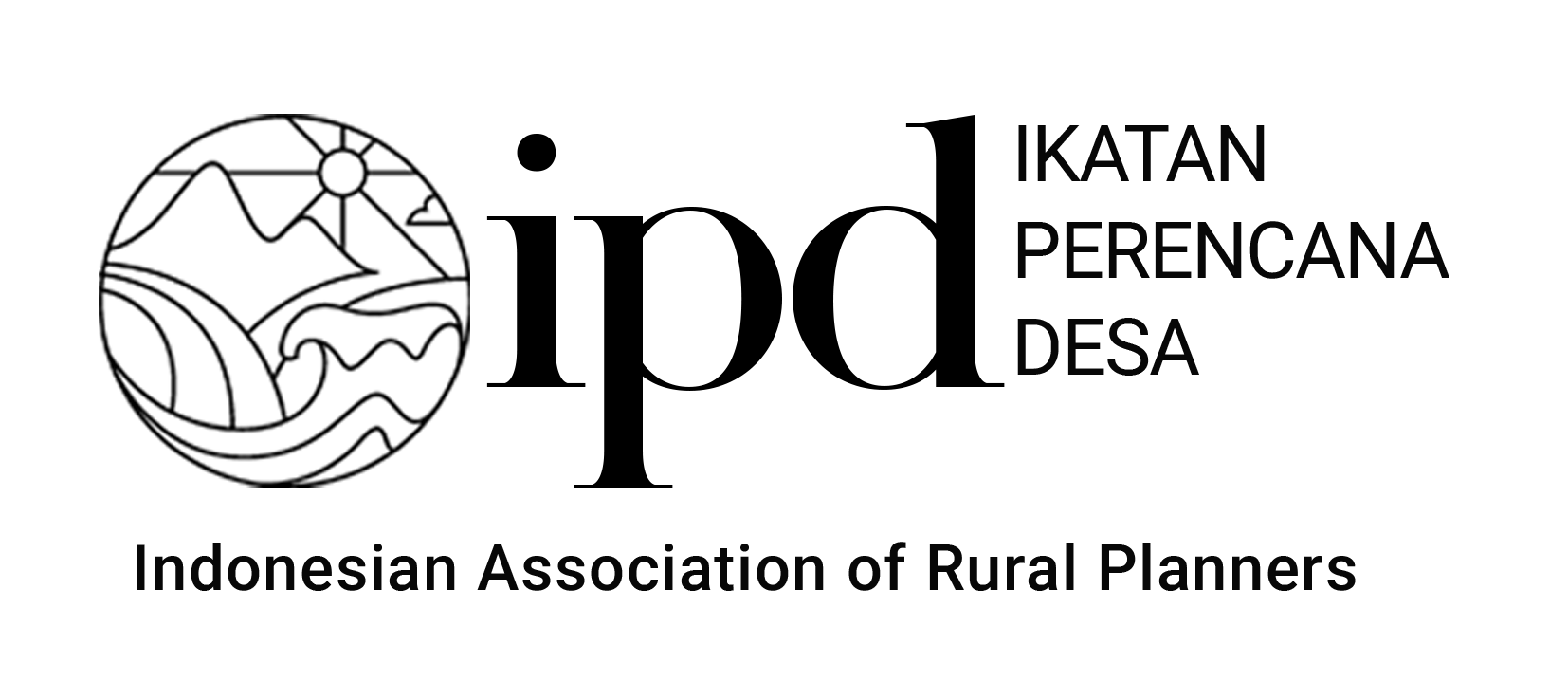Siklus Remitan Mudik dan Pembangunan Desa

Setiap tahun, gelombang mudik Lebaran membawa aliran dana segar ke pedesaan Indonesia. Bank Indonesia memperkirakan total remitansi mudik 2024 mencapai Rp150 triliun (BI, 2024), angka yang hampir menyamai total anggaran Dana Desa tahun ini. Namun, ironisnya, 70% dari dana tersebut hanya berputar dalam siklus konsumsi jangka pendek---untuk belanja kebutuhan Lebaran, renovasi rumah, atau pembelian barang-barang elektronik (LPEM UI, 2023). Padahal, jika dikelola secara produktif, potensi dana mudik ini bisa menjadi mesin penggerak pembangunan desa yang lebih berkelanjutan.
Fenomena ini terlihat jelas di Desa Pringgasela, Lombok Timur, sentra tenun tradisional Sasak. Data BPS NTB (2024) menunjukkan bahwa meskipun pemudik membawa rata-rata Rp7 juta per orang, hanya 15% yang diinvestasikan kembali ke usaha tenun. Sebagian besar digunakan untuk membeli motor (35%) dan peralatan elektronik (25%). Padahal, dengan modal Rp5 juta saja, seorang pengrajin bisa membeli alat tenun semi-mekanis yang mampu meningkatkan produktivitas hingga 300% (Kemenperin, 2023). Kondisi serupa terjadi di sentra-sentra produksi pertanian seperti Brebes (bawang merah) dan Garut (kopi), di mana remitansi mudik jarang digunakan untuk pengembangan usaha tani.
Studi komparatif menarik datang dari Filipina. Menurut laporan Asian Development Bank (2023), 40% remitansi pekerja migran Filipina diinvestasikan dalam sektor produktif, berkat sistem "collective remittance" melalui koperasi. Mekanisme ini memungkinkan dana-dana kecil digabungkan menjadi modal yang cukup besar untuk membiayai proyek-proyek komunitas. Di Indonesia, praktik serupa sebenarnya sudah ada, tetapi dalam skala terbatas. Di Banyuwangi, program "Tabungan Mudik" yang diinisiasi Koperasi Tani Makmur berhasil mengumpulkan Rp2,8 miliar dari 560 pemudik pada 2023, yang kemudian dipinjamkan kepada anggota untuk pengembangan usaha pertanian organik (Jurnal Ekonomi Desa, 2024).
Persoalan mendasar terletak pada tiga hal. Pertama, minimnya akses ke lembaga keuangan di pedesaan. Data OJK (2024) menunjukkan bahwa 60% desa di Indonesia masih termasuk dalam kategori "banking desert", dengan akses terbatas ke produk keuangan formal. Kedua, kurangnya edukasi keuangan. Survei Bappenas (2023) menemukan bahwa 75% pemudik tidak pernah mendapat informasi tentang cara mengelola remitansi secara produktif. Ketiga, lemahnya ekosistem pendukung. Di Desa Cibuntu, Jawa Barat, misalnya, para perantau yang ingin berinvestasi di usaha peternakan kesulitan mendapatkan pendampingan teknis (Kompas, 2024).
Lalu, bagaimana mengubah pola ini? Pertama, pemerintah perlu mengembangkan program "Remitansi Produktif" dengan insentif konkret. Skema bisa berupa matching fund, di mana setiap Rp1 juta yang diinvestasikan pemudik ke koperasi/UMKM desa akan ditambah Rp500 ribu oleh pemerintah. Model ini sukses diterapkan di Kabupaten Jember untuk pengembangan usaha susu sapi perah (Jawa Pos, 2023).
Kedua, penting untuk memperkuat peran fintech dalam penyaluran remitansi. Di era di mana 65% pemudik sudah menggunakan dompet digital (OJK, 2024), platform seperti LinkAja atau DANA bisa diintegrasikan dengan produk investasi mikro. Misalnya, dengan membuat fitur "Investasi Desa" yang memungkinkan pemudik mengalokasikan sebagian dananya untuk pembiayaan UMKM lokal dengan bagi hasil.
Ketiga, perlu dibangun sistem pendampingan terpadu. Kolaborasi antara penyuluh pertanian, akademisi, dan praktisi bisnis bisa membantu mengubah remitansi menjadi usaha yang viable. Di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, program pendampingan oleh Universitas Hasanuddin berhasil membantu 120 keluarga pemudik mengembangkan usaha olahan cokelat dengan omset Rp15 juta per bulan (Koran Tempo, 2024).
Kebijakan konkret yang bisa segera diimplementasikan, diantaranya Tax incentive bagi pekerja yang menginvestasikan remitansinya di desa, Pelatihan pengelolaan remitansi wajib bagi calon TKI/TKW sebelum keberangkatan, dan Peta potensi investasi desa yang memudahkan pemudik mengidentifikasi peluang usaha.
Seperti dikemukakan oleh ekonom Muhammad Tadjuddin (2023), "Remitansi mudik ibarat hujan deras di musim kemarau---bisa menggenangi permukaan tanah tanpa meresap ke akar." Sudah waktunya kita membangun sistem resapan yang mampu mengubah aliran dana musiman ini menjadi sumber air yang menghidupi pembangunan desa sepanjang tahun.
Untuk membaca opini lengkapnya, kunjungi Kompasiana.